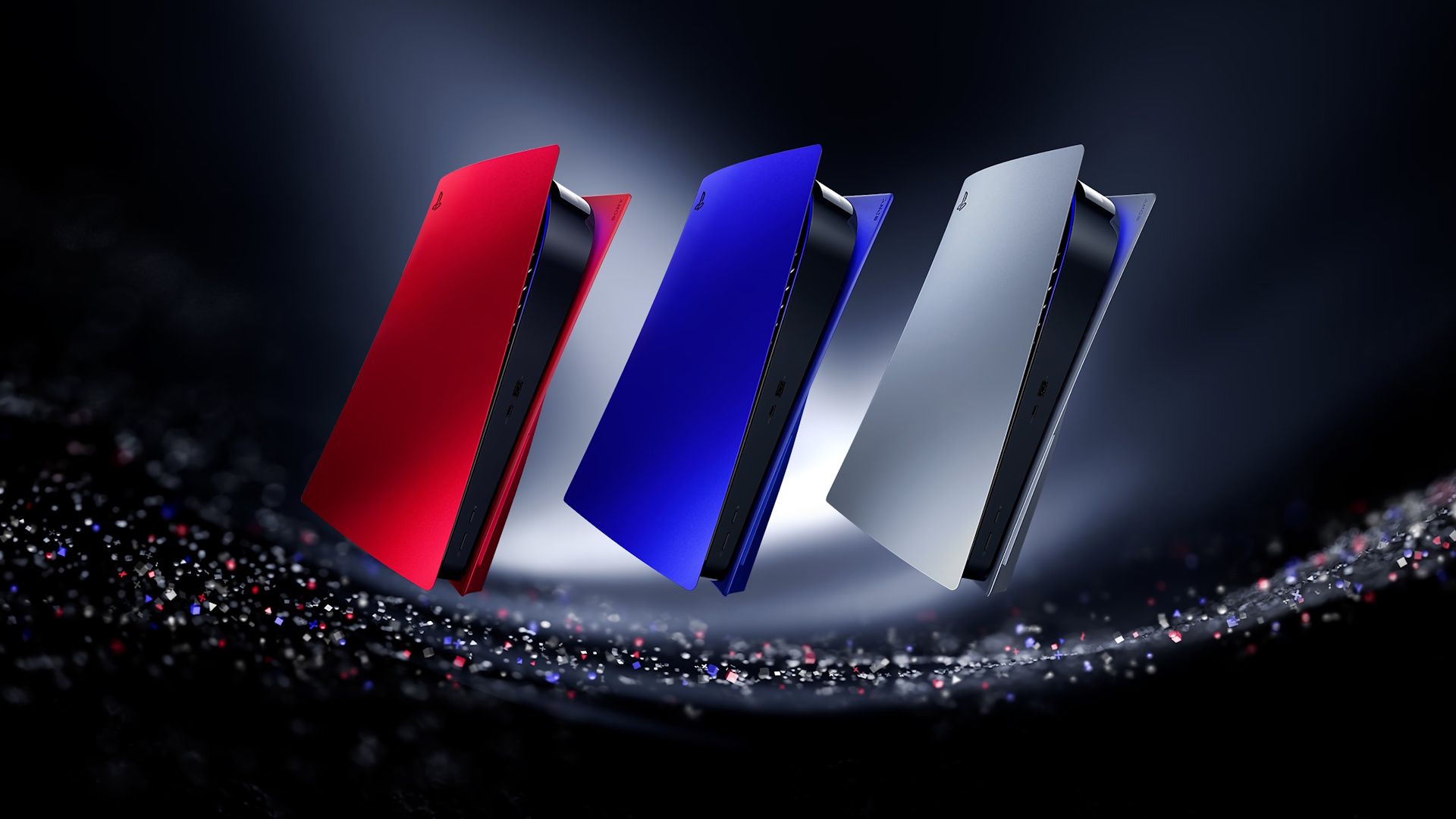Penulis ini, yang sebelumnya membela adaptasi pertama Five Nights at Freddy’s 2, kini menyatakan kekecewaannya yang mendalam terhadap sekuel film tersebut. Five Nights at Freddy’s 2 Review mengungkap bahwa film ini membawa kembali animatronik mengesankan dari Henson Company, namun terikat pada cerita yang buruk, yang meremehkan perbedaan besar antara medium video game dan film. Hal ini menjadikan film horor PG-13 ini sebagai langkah mundur yang signifikan.
Animatronik Mengesankan dan Skor Musik Khas
Meskipun kritik tajam menyertai sekuel ini, aspek animatronik menjadi satu-satunya sorotan positif. Jim Henson’s Creature Shop kembali menggandakan kehadirannya dengan menyertakan versi “Toy” dari geng Freddy. Versi yang lebih ramping dan metalik ini sama mengesankannya dengan iterasi Chuck E. Cheese yang lebih berbulu dari film sebelumnya.
Efek praktis yang disajikan tetap menjadi mahakarya, memperlihatkan dominasi dalam penciptaan karakter. Misalnya, bentuk “Mangle” Foxy, yang merupakan eksperimen aktivitas bongkar pasang yang gagal, menampilkan penampilan seperti rongsokan yang mengerikan. Sementara itu, The Marionette yang tergantung dan melambai dengan keanehan seperti mie, berlawanan dengan gerakan robotik Freddy.
Sutradara Tammi dinilai mampu menghidupkan para raksasa yang tidak terlalu lembut ini dengan daya tarik yang luar biasa. Selain animatronik, skor musik karya The Newton Brothers juga mendapat pujian. Terinspirasi dari soundtrack 8-bit dan lagu-lagu restoran anak-anak yang ceria, musiknya berhasil menangkap esensi unik dari waralaba Five Nights at Freddy’s.
Adaptasi Gameplay yang Tergelincir
Penggemar berat Fazbear mungkin sudah bisa menebak apa yang akan disajikan dalam Five Nights at Freddy’s 2. Pencipta game, Cawthon, lebih peduli untuk memamerkan “hit” daripada merombak konsep dasar “petugas keamanan di ruangan” yang menjadi ciri khas gameplay-nya. Tammi, sang sutradara, terbebani oleh naskah yang dijejali Easter egg tanpa nutrisi, seolah penonton disandera di fasilitas produksi Cadbury.
Meskipun ada momen lucu seperti Josh Hutcherson yang mengejek faceplate Freddy yang dibuang dan kemudian benda itu benar-benar berfungsi sebagai penyamaran, film pertama jauh lebih cerdik dalam mengubah gaya bermain Five Nights at Freddy’s yang statis menjadi petualangan berdurasi panjang. Film pendahulunya tidak banyak menuruti keinginan penggemar, melainkan merevolusi gameplay untuk sinema.
Dalam hal ini, Five Nights at Freddy’s 2 justru menjadi kemunduran. Film ini mencoba mengadaptasi elemen gameplay satu per satu tanpa menyadari betapa konyolnya fungsionalitas tersebut terlihat di layar lebar. Pendekatan ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang bagaimana elemen interaktif game dapat diterjemahkan secara efektif ke dalam narasi film.
Teror dan Jumpscare yang Redundant
Tammi dan Cawthon berupaya memberikan gigitan horor yang lebih ganas, namun mereka hanya mengandalkan satu metode: jump scares. Meskipun Cawthon memperkenalkan The Marionette sebagai penjahat yang mirip boneka kaus kaki, yang dapat merasuki manusia dan mengubah mereka menjadi iblis bermata cerah, film ini menggunakan citra yang menyeramkan itu dengan cara yang tidak efektif.
Penulis sebelumnya telah membahas seni jump scare, menekankan bahwa itu seharusnya menjadi tambahan, bukan hidangan utama dalam horor. Sayangnya, Five Nights at Freddy’s 2 tidak sependapat, dan hasilnya adalah film yang kehilangan daya menakutinya.
Film ini cenderung menggunakan tropi horor PG-13 yang paling tidak menarik, di mana semua hal menarik terjadi di luar layar. Jump scares digunakan berulang kali hingga menjadi berlebihan dan mudah diprediksi. Ditambah lagi dengan filter wajah ala Instagram yang buruk saat Charlotte merasuki tubuh seseorang, upaya film untuk menjadi lebih menyeramkan terasa gagal total dan tidak memberikan efek apa pun.
Masalah Narasi dan Aksi Ketiga
Secara keseluruhan, Five Nights at Freddy’s 2 terasa sangat sadar diri dan reaksioner. Cawthon mencoba mengatasi keluhan sebelum muncul, yang seringkali menjadi resep kegagalan. Meskipun film Five Nights at Freddy’s pertama secara brutal dihujani kritik, langkah mundur ini terasa seperti tindakan pengecut.
Sekuel ini melakukan semua kesalahan adaptasi video game yang sudah sering kita lihat sebelumnya, yang terasa lebih menyakitkan karena pendahulunya tidak melakukan hal serupa. Waralaba game ini sendiri adalah kekacauan kontinuitas yang rumit, dan kekacauan ini kini mulai meresap ke dalam film-film Blumhouse.
Kecerobohan narasi semacam itu mungkin lebih bisa dimaafkan dalam video game, di mana interaktivitas mengungguli penceritaan. Namun, film adalah media yang berbeda. Tanpa arahan yang kuat, Cawthon kembali ke pola pikir video game yang tidak berfungsi sama di Hollywood.
Yang terburuk dari semua itu, Five Nights at Freddy’s 2 menderita masalah di babak ketiga. Bahkan, bisa dibilang film ini tidak memiliki babak ketiga yang jelas. Cawthon memperlakukan sekuel ini sebagai materi promosi berdurasi penuh untuk apa pun yang akan datang selanjutnya. Karakter The Marionette layak mendapatkan pengembangan yang lebih baik daripada yang diberikan film ini.
Film ini terlalu banyak membangun fondasi tanpa keinginan untuk menyelesaikan apa pun. “Jangan khawatir, itu semua akan ditangani di sekuel,” seolah-olah Blumhouse berjanji sambil menghitung tumpukan penjualan tiket. Cawthon membombardir penonton dengan lore dan menabur garam di luka lama, menghadirkan pengungkapan demi pengungkapan sebelum kesimpulan yang singkat dan menunjukkan kurangnya pemahaman mendasar tentang struktur film.
Film ini mati-matian menginginkan penonton terkejut dengan akhir yang menggantung, namun yang terjadi justru membuat penonton ingin memutuskan hubungan dengan seri yang kacau ini. Rasanya seperti sebuah “game over, cabut steker, reboot sistem” untuk pengalaman sinematik ini.
Performa Akting dan Karakterisasi
Para aktor berjuang mati-matian untuk menampilkan sedikit pun intrik dari peran mereka, namun dialog dan situasi yang ada terasa kurang meyakinkan. Lail, sebagai putri yang tersiksa, mencoba mengubur penonton dalam trauma Vanessa. Namun, adegannya yang tiba-tiba menodongkan pistol ke teman kelas spin-nya di tengah-tengah krisis, tidak dirancang untuk membuat penonton tertawa.
Josh Hutcherson digambarkan mengembara tanpa tujuan di sepanjang sekuel, mengisi kekosongan di mana pun ia dibutuhkan. Kemudian ada Rubio, korban perundungan orang dewasa oleh guru sainsnya karena adanya kompetisi robotik penting pada hari yang sama dengan festival Freddy Fazbear di seluruh kota. Plot-plot ini terasa dibuat-buat dan terkesan serampangan.
Aktor pendukung seperti Skeet Ulrich, Mckenna Grace, Wayne Knight, dan Theodus Crane semuanya layak mendapatkan peran yang lebih baik dalam Five Nights at Freddy’s 2. Peran mereka berkisar dari pemicu kemarahan hingga sekadar karakter sampingan tanpa nama, menunjukkan kurangnya pengembangan karakter yang berarti.
Kesimpulan: Sekuel Minim dan Mengecewakan
Terus terang, Five Nights at Freddy’s 2 adalah sekuel yang tampil minim. Setiap elemen yang disajikan terasa kurang antusias. Sebagai film horor, ia dengan malas mendorong karakter langsung menuju bahaya, membiarkan mereka di sana secara bodoh, dan merusak ketegangan dengan mengisyaratkan setiap scare.
Sebagai adaptasi video game, film ini memamerkan mekanisme dan callback yang familiar—tombol merah dan hijau! Balloon Boy!—namun memperlakukan elemen-elemen ini sebagai daya tarik utama, bukan bagian dari cerita yang kohesif. Ini adalah sekuel yang tidak lengkap, cerita tentang masa remaja yang kurang ditulis, dan sebagai film horor PG-13, ia akan ditertawakan oleh film-film seperti Insidious atau Scary Stories to Tell in the Dark di mata kritikus.
Pesan penutup yang terasa adalah “Game over, cabut steker, reboot sistem,” menandakan kegagalan total dalam menyampaikan pengalaman yang memuaskan dari sebuah Five Nights at Freddy’s 2 Review.
Video Terkait
10 Ways Movies Terrify Us (And 75 Movies That Prove It) | A CineFix Movie List